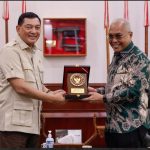Oleh: Imam Ridho Angga Yuwono, SH.,MH.
Penulis adalah Divisi Hukum Komite Rakyat Buton.
BAUBAU, Rubriksultra.com- Sebagaimana penjelasan dibeberapa pertemuan-pertemuan baik yang bersifat formal ataupun koja-koja, perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dari para sesepuh dan tokoh-tokoh politik di wilayah jazirah Kepulauan Buton telah didengungkan sejak ± sekitar tahun 2009. Awalnya rencana pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 itu, digagas dengan platform perjuangan Pemekaran Provinsi Buton Raya, namun pada akhir tahun 2014 berubah menjadi perjuangan “Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton” disesuaikan dengan political will dari elit-elit politik daerah yang menjadi cakupan wilayah Provinsi Kepulauan Buton.
Masalah utama pemekaran Provinsi Buton Raya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam kurun waktu ± tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah terhambat oleh syarat dasar pemekaran wilayah, yakni masalah wilayah cakupan daerah Provinsi. Keluarnya Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna dari wilayah cakupan Provinsi Buton Raya menyisakan 4 Kabupaten/Kota yang masih konsisten menjadi wilayah cakupan Provinsi Buton Raya, 4 wilayah tersebut adalah Kota Baubau, Kabupaten Buton,
Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Buton Utara. Tentu saja kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 sebagai acuan hukum bagi proses pemekaran wilayah dikala itu yang meng-amanahkan wilayah cakupan Daerah Provinsi minimal berjumlah lima Kabupaten/Kota.
Dengan lahirnya Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah, pada akhirnya Provinsi Kepulauan Buton telah memenuhi jumlah wilayah cakupan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Adapun wilayah cakupan Provinsi Kepulauan Buton adalah sebagai berikut:
| 1. | Kota Baubau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 dan ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2001; |
| 2. | Kabupaten Buton dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan ditetapkan pada tanggal 4 juli 1959; |
| 3. | Kabupaten Wakatobi yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2003 dan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003; |
| 4. | Kabupaten Buton Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 dan ditetapkan pada tanggal 2 januari 2007; |
| 5. | Kabupaten Buton Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2014; serta |
| 6. | Kabupaten Buton Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2014. |
Masih berdasarkan informasi dari Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai representatif dari komponen masyarakat Provinsi Kepulauan Buton Raya, pengusulan Persiapan Daerah Otonomi Baru Provinsi Kepulauan Buton selain telah memenuhi persyaratan dasar juga telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana maksud ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPD. Namun menurut Sekber, hambatan utama perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton sehingga belum mendapat kejelasan sampai saat ini adalah sama dengan daerah lain, yaitu political will pemerintah pusat yang saat ini menerapkan kebijakan moratorium terhadap usulan daerah otonomi baru.
Salah satu siasat pemerintah pusat dala kebijakan moratorium tersebut adalah dengan sementara terbitnya PP sebagai peraturan pelaksa ketentuan penataan daerah dalam UUPD. Siasat dengan menahan sementara peraturan pelaksana saat ini, tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan yang menjelaskan: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
Adapun ketentuan dalam UUPD yang mewajibkan pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap ketentuan penataan daerah adalah:
| a. | Pasal 35 ayat (2) yang menjelaskan, “ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah”; |
| b. | Pasal 39 ayat (6) yang menjelaskan, “ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah”; |
| c. | Pasal 55 yang menjelaskan, “ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah”; |
| d. | Dan Pasal 56 yang menjelaskan, “desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah”; |
Jimly Asshiddie dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi” menegaskan, bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (Rectsstaat), bukan negara kekuasaan (macstsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pembagian dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakekatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi (nomocracy) dan doktrin “the rule of law, and not of man”. Dalam kerangka the rule of law itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of law).
Bila dihubungkan dengan pendapat Jimly Asshidiqie di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah pusat tidak tepat dalam hal menerapkan suatu kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Penundaan sementara penerbitan Peraturan Pelaksanaan tentang Penataan Daerah bisa saja dianggap sebagai suatu penerapan konsep Negara berdasarkan kekuasaan (macstsstaat), karena tidak berdasarkan perundang-undangan sebagai rujukan hukum paling utama di negara yang kita cintai ini.
Penulis sendiri berpendapat bahwa, sebenarnya pada suatu negara yang memiliki budaya hukum legalistic, undang-undang wajib dianggap mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perbuatan hukum terkait dengan materi dan muatan dalam peraturan tersebut. Selain itu, pada hakikatnya UUPD telah menampung kehendak penuh semua pemangku kepentingan serta telah menampung rasa keadilan dan kemanfaatan jika diterapkan. Oleh karena itu penulis berkesimpulan, sebenarnya tidak ada satupun alasan hukum bagi pemerintah pusat untuk melakukan penundaan penerbitan peraturan pelaksanaan tentang penataan daerah.
Asumsi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
PROBLEM HUKUM DALAM PENATAAN DAERAH
Sebenarnya dalam terminology hukum sendiri, tidak dikenal istilah moratorium. Istilah moratorium adalah suatu narasi yang dibangun dan digunakan untuk menangguhkan suatu hutang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. Namun bila disandingkan dalam terminology Hukum Tata Negara, istilah moratorium dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan Negara yang tentu saja kebijakan tersebut harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya, dalam tata administrasi pemerintah Negara Indonesia kebijakan Pemerintah wajib diwujudkan melalui suatu keputusan atau tindakan yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Bertolak pada sikap DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat yang telah berulang kali mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP pelaksanaan dari UUPD terkait ketentuan penataan daerah namun pemerintah tidak bergeming dan segera mengambil suatu keputusan atau tindakan untuk menerbitkan peraturan tersebut dengan alasan moratorium, menurut hemat penulis moratorium yang disebut-sebut oleh pemerintah itu dapat diklasifikasikan sebagai sikap diam dari pemerintah pusat yang menolak menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait ketentuan penataan daerah, atau dalam system tata administrasi pemerintahan disebut dengan suatu keputusan yang bersifat fiktif negatif.
Pada sikap pemerintah semacam itu, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, yaitu melalui gugatan tata usaha negara atau gugatan citizen lawsuit melalui Pengadilan Negeri. Namun, bilamana upaya hukum tersebut dilaksanakan masalah hukum berikutnya adalah Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan umum dan tata usaha negara dipaksa untuk membuat suatu penemuan hukum (rechtsvinding) yang kebablasan bila mengabulkan tuntutan penggugat dengan menghukum pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait ketentuan penataan daerah dalam waktu tertentu. Tentu saja upaya hukum tersebut akan banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan para sarjana hukum.
Atau bahkan sebaliknya karena MA tidak berani membuat suatu terobosan hukum tersebut, dan menganggap tindakan atau keputusan pemerintah pusat yang menolak menerbitkan peraturan pelaksanaan tersebut adalah benar menurut hukum karena telah lewat waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 410 UUPD. Oleh karena itu menurut hemat penulis, gugatan tata usaha negara dan citizen lawsuit bukanlah solusi terhadap masalah ini.
Problem selanjutnya, meskipun dalam hal ini pemerintah pusat tidak menolak menerbitkan peraturan pelaksanaan tetapi hanya menunda sementara, peraturan pelaksanaan terkait penataan daerah yang akan diterbitkan mengandung cacat secara yuridis karena telah melampaui waktu yang ditentukan oleh perundangundangan. Kondisi hukum semacam itu, membuka peluang bagi daerah-daerah yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan dengan terbitnya peraturan pelaksanaan tersebut untuk melakukan upaya yudisial review terhadap ketentuan perundangundangan di bawah undang-undang kepada MA. Salah satu alasan upaya yudisial review tersebut adalah peraturan pelaksanaan terkait penataan daerah yang akan diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 410 UUPD, sehingga peraturan pelaksanaan terkait penataan daerah yang diterbitkan pada akhirnya diputus inkonstitusional.
Kedua problem hukum yang dijelaskan di atas, selain dapat merugikan kepentingan perjuangan pemekaran provinsi Kepulauan Buton karena tarik ulurnya persoalan hukum yang akan memakan waktu lama dan tidak dapat ditentukan. Menurut penulis, kedua problem hukum tersebut juga menjadi ke-bimbangan bagi pemerintah pusat dalam menentukan pilihan, apakah segera menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait Penataan Daerah atau menundanya sampai terjadi perubahan regulasi terkait waktu penerbitan peraturan pelaksanaan tersebut. Ke-bimbangan pemerintah pusat tersebut-pun secara politis bukan tanpa alasan, persaingan antar daerah yang mengusulkan pemekaran namun tidak diatur dengan rambu-rambu yang benar dapat menyebabkan chaos dan mengganggu stabilitas nasional.
Masih menurut penulis juga, problem hukum di atas terjadi akibat Pemerintah Pusat salah mendudukan kebijakan moratorium pemekaran daerah yang selama ini disebut-sebut menjadi penghalang pelaksanaan pemekaran daerah. Seharusnya kebijakan moratorium pemekaran daerah diterapkan pada fase evaluasi terhadap daerah persiapan sebagaimana diatur pada Pasal 52 dan 53 UUPD. Kebijakan moratorium tersebut semestinya diarahkan kepada daerah-daerah yang telah menjadi daerah persiapan, agar dalam jangka waktu persiapannya ada suatu tekanan bagi daerah yang dipersiapkan tersebut untuk mampu menjadi daerah yang mandiri dan dapat menyesuaikan kondisi keuangan negara atau bahkan memberi kontribusi terhadap keuangan Negara.
Seharusnya pemerintah pusat menerapkan setrategi antrean. Negara dapat memutuskan sejumlah daerah secara terbatas untuk masuk sebagai daerah persiapan berdasarkan kemampuan keuangan negara, lalu pemerintah pusat meng-evaluasi dengan standart penilaian daerah persiapan tersebut nantinya tidak membebani keuangan negara. Bagi daerah yang tidak lolos pada fase evaluasi seperti itu, pemerintah pusat menerapkan moratorium dan mengembalikan kepada daerah induk. Konsep kebijakan tersebut dapat memberikan solusi terhadap desakan dari daerah-daerah yang mengusulkan untuk dimekarkan.
Sayangnya yang terjadi saat ini adalah sebaliknya, terbangun suatu prespektif seolah-olah secara kolektif seluruh daerah pengusul akan dimekarkan, tentu saja yang berada dibenak masyarakat keadaan tersebut membebani keuangan negara.
SOLUSI
Berdasarkan masalah-masalah hukum yang telah dijelaskan di atas, solusi yang tepat bagi pemerintah pusat adalah mendapatkan suatu kepastian hukum apakah peraturan pelaksanaan terkait penataan daerah dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat atau tidak sama sekali. Bagi penulis, demi kepentingan tertibnya penyelenggaraan pemekaran daerah, pemerintah pusat harus diberi kesempatan sekali lagi oleh hukum untuk dapat menetapkan peraturan pelaksanaan penataan daerah dengan syarat waktu tertentu.
Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yudisial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 35 ayat (2), 39 ayat (6), 55 dan 56 atau, legislasi review melalui DPR RI terhadap Pasal 410 UUPD. Sebagai praktisi hukum, penulis lebih memilih untuk melakukan yudisial review di MK dengan pertimbangan kepraktisan dan efektifnya waktu.
Isu hukum yang dapat digunakan pada proses yudisial review di MK terhadap Pasal 35 ayat (2), 39 ayat (6), 55 dan 56, secara pokok adalah menuntut pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan waktu oleh MK, agar negara memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan dari UUPD terkait ketentuan penataan daerah dalam rentan waktu yang ditentukan oleh MK.
Setidaknya dapat menjadi contoh bahwa dibeberapa putusannya, MK memberikan jangka waktu penerapan dalam suatu norma perundang-undangan, salah satunya putusan perkara nomor 79/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”.
Tak kalah pentingnya pula dalam melakukan yudisial review di MK, Pemohon wajib memperhatikan syarat keterpenuhan kepentingan hukum (legal standing) sebagai permohon dalam pengujian undang-undang. Pasal 38 ayat (1) UUPD menyebutkan: “Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37”. Menurut penulis pasal tersebut secara limitatif telah membatasi kepentingan hukum pemohon pengujian ketentuan undangundang terkait penataan daerah, ketentuan tersebut memberikan kewajiban dalam pemenuhan persyaratan secara khusus kepada gubernur. Oleh karena itu legal standing yang tepat dalam yudisial review di MK berada pada gubernur.
Lalu bagaimana dengan kepentingan hukum pemohon pengujian undang-undang bagi perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton?. Di dalam surat usulan pemekaran provinsi kepada pemerintah pusat yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Tenggara, telah menyertakan Sekber sebagai salah satu komponen yang turut melengkapi persyaratan administrasi dalam pengusulan pemekaran tersebut. Oleh karena itu penulis berpendapat Ketua Sekber juga memiliki kepentingan hukum sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang terkait ketentuan penataan daerah.
PENUTUP
Demikian telaah persoalan hukum Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton yang penulis buat secara singkat, semoga dapat memberikan solusi terhadap kebuntuan yang saat ini dialami dalam perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton. Mohon maaf atas segala kekurangan. (***)